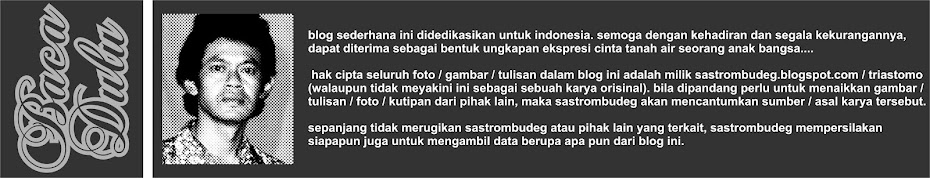http://sastrombudeg.blogspot.com
Wayang sebagai bagian seni pentas, baik itu wayang orang, kulit, ataupun golek, yang dalam perkisahannya identik dengan fragmen-fragmen Ramayana dan Mahabarata, dari waktu ke waktu berada dalam rel dinamika penyikapan terhadap lingkungan dan budaya yang men’zamani’nya.
Kiranya salah besar apabila kemudian terjadi polemik tentang pergeseran nilai-nilai kewayangan, sebagaimana pernah terjadi pada dekade delapan puluhan sampai sembilan puluhan. Para budayawan Jawa (dari berbagai kalangan) gagal mencapai kesimpulan dan membuat formula bagaimana cara ‘mengunci’ wayang di dalam satu kotak pandora bernama “pakem’. Bagaimana seni pewayangan menjadi benda pusaka suci yang tidak boleh disentuh oleh peradaban selanjutnya. Wayang harus ‘seolah-olah’ menjadi saksi bisu suatu ‘kemandegan’ proses berbudaya suatu bangsa.
Saat itulah, dalang-dalang, para sinden, dan niyaga dituntut berperan sebagai mayat-mayat yang bangkit dari kubur: anyir, kaku, bisu, dan pucat. Dan penontonnya pun dapat dipastikan hanyalah orang-orang yang bernyali untuk duduk bersila di atas tikar penonton di balik 'geber' (layar) sampai kokok ayam jantan di subuh buta menyadarkannya.
Untung, masyarakat pecinta dan pelaku dalam pentas-pentas wayang jalan terus dan tidak perduli dengan kertas kerja-kertas kerja mereka. Masyarakat yang terintegrasi dalam kehidupan dan penghidupan di dalam pentas-pentas wayang tidak 'mood' dengan idiom-idiom pewayangan hasil rekayasa para pengamat atau budayawan.
Salah satu pemicu ‘kegelisahan’ para budayawan saat itu adalah Ki Nartosabdo. Dalang yang besar di Semarang itu pada tahun tujuh puluh-delapan puluhan mengemas wayang menjadi ‘pakeliran padhet’. Pementasannya tak lebih dari lima-enam jam, beda dengan wayang sebelumnya yang bisa mencapai dua belas jam! Lebih ekstrim lagi, bekas muridnya, Ki Manteb Soedarsono, yang bahkan bisa (baca: berani) melakukan pentas hanya untuk waktu tayang dalam hitungan di bawah satu jam saja!
Sesungguhnya, yang terjadi kala itu hanyalah ekspresi rasa kekhawatiran terhadap pergeseran nilai-nilai orisinalitas wayang. Ada yang ‘dipaksakan’ untuk dilupakan bahwa wayang mempunyai sejarah kreatif dan berasal dari suatu proses yang membutuhkan kurun waktu hingga terbentuk menjadi seperti sekarang ini.
Ada kehendak sebagian budayawan untuk membakukan (mem’pakem’kan) wayang. Mereka lupa bahwa kondisi kita saat ini seringkali tidak pas untuk menjadi penonton wayang model baku dan ‘orisinal’ seperti yang mereka inginkan. Mereka sengaja mencoba dan berusaha memuntir fakta sejarah bahwa awal sebuah wayang adalah juga bukan bersumber pada sebuah orisinalitas. Karena sebagian komponen di dalamnya terdapat barang impor dari India (kisah Ramayana dan Mahabarata), yang bahkan juga tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat Hindu India sebagai sebuah ‘pembajakan’.
Dari situ, maka sebagai langkah ‘damai’ antara pihak yang propakem (idealis) dan pihak pelaku seni pewayangan propasar (realistis), dibuatlah bermacam-macam karakter pementasan wayang; wayang klasik, wayang pop, wayang popndut, dan sebagainya. Semua tinggal mana selera kita.
Kritik Sosial pada Pementasan Wayang
Seperti halnya pada seni sastra, seni rupa, seni musik, dan seni pertunjukan lainnya, wayang secara terus-menerus juga melahirkan kreativitas baru dan dinamis sebagai bentuk penyikapan terhadap laju peradaban manusia. Seni tidak bisa lepas dari peradaban manusia. Peradaban manusia tidak bisa lepas dari seni.
 Kritik-kritik sosial dan ‘pemberontakan’ terhadap suatu keadaan tertentu yang mengganggu nurani humaniora seringkali lahir dan diungkapkan melalui seni. Wayang dengan bijaksana telah meletakkan ruang ‘mimbar rakyat’ dalam ‘pakem’ pementasannya melalui Punakawan dan Limbuk yang eksis di sesi ‘Goro-goro’ . Sebuah sesi yang selama ini dianggap sebagai sesi yang tidak penting dan hanya menjadi embel-embel pencegah kantuk. Biasanya muncul setelah jam dua belas malam.
Kritik-kritik sosial dan ‘pemberontakan’ terhadap suatu keadaan tertentu yang mengganggu nurani humaniora seringkali lahir dan diungkapkan melalui seni. Wayang dengan bijaksana telah meletakkan ruang ‘mimbar rakyat’ dalam ‘pakem’ pementasannya melalui Punakawan dan Limbuk yang eksis di sesi ‘Goro-goro’ . Sebuah sesi yang selama ini dianggap sebagai sesi yang tidak penting dan hanya menjadi embel-embel pencegah kantuk. Biasanya muncul setelah jam dua belas malam.
‘Mimbar rakyat’ tersebut pada tengah dekade sembilan puluhan telah digarap lebih ‘berani’ dan diberdayakan oleh para dalang senior yang telah sampai pada puncak ‘kekesalan’ terhadap perilaku rezim Orde Baru. Pemberdayaan sesi ini pada kenyataannya seringkali justru ditunggu para penikmatnya, lebih nge’pop’ mengalahkan jalan cerita utama.
‘Mimbar rakyat’ tak melulu ‘guyon maton’ (asal humor), tapi digarap sebagai arena melontar kritikan. Bahwa seni pewayangan ber’roh’kan ajaran dari kitab Ramayana dan Mahabarata dan notabene berisi tuntunan hidup (hitam-putih, baik-buruk, jujur-bohong, adil-curang, dan lain sebagainya), ternyata dianggap tidak mempan lagi sebagai suluh pengembali nurani kebenaran dan keadilan yang di belakangnya berlaku ‘karma hasil perbuatan’.
‘Mimbar bebas’ ala wayang telah menjadi ruang untuk memuntahkan ‘kemarahan moral’ sang dalang. Dikemas dalam bahasa ‘rakyat’ dalam suasana ‘rakyat’ pula. Jiwa rakyat diserapnya, dihayatinya, direfleksikannya, dan diletupkan sedemikian rupa dalam bahasa kritik yang sungguh me’nyudra’. Tak heran bila di mana-mana menuai aplus dan ‘ger’ dari segala lapisan masyarakat penikmat wayang. Para pejabat pada saat itu pun juga turut hanyut dalam arus ger-geran, tak sadar bahwa mereka juga menjadi salah satu sasaran tembaknya.
Menjelang Reformasi 1998 dan sesudahnya, adalah Ki Manteb Soedarsono, sebagai salah satu motor gerakan ‘mimbar bebas’ ala wayang. Lugas, cerdas, dan sarkas. Tentang ini, penulis yang berada di daerah transmigrasi saat itu, memonitor pentas-pentas Ki Manteb Soedarsono melalui RRI Pusat Jakarta yang tiap malam Minggu menyiarkan secara live pentas wayang kulit diselang-seling dengan wayang golek.
Telah lazim bahwa pentas wayang sebelum genre Ki Nartosabdo merupakan pengabdi kesantunan tutur tradisi Jawa yang penuh perlambang dan pesan-pesan luhur. Wayang sebagai media komunikasi yang berisi tuntunan penuh filosofi Jawa relatif terjaga. Namun di tangan Ki Manteb Sudarsono, monotonitas seperti di atas serta merta bisa raib dan berubah menjadi dramatis, sarkas, ‘nyelekit’, dan ekspresif (dari sebuah sumber, dramatika pewayangan menjadi roh yang memikat semenjak Ki Nartosabdo memperoleh pembelajaran dari dalang Ki Wignyo Sutarno).
Wayang adalah wayang. Dalang tetaplah pengendalinya. Idealisme lakon seakan-akan menjadi hak mutlak sang dalang, di luar standar minimal agar sebuah wayang kulit tetap disebut pementasan wayang kulit. Sudah barang tentu.
Penulis bukanlah orang yang paham dengan dunia wayang. Maka mohon dimaafkan bila terdapat kekeliruan dalam penganalisaan sejarah wayang. Penulis tergoda untuk menulis ini, karena setahu penulis, bahasa tuntunan dalam pementasan wayang ‘klasik’ cenderung halus dan terjaga kesopanannya, yang pada awal-awal Reformasi 1998 hingga sekarang terasa berubah menjadi ‘binal’ dan ‘liar’.
Mungkinkah zaman yang menghendaki demikian?
Para pemimpin, pemegang otoritas politik, hukum, ekonomi, pendidikan, serta agama seakan ‘budeg’ dan ‘ndableg’. Atau bahkan ‘menantang’! Pendek kata, dengan tuntunan halus (sindiran) ala wayang ‘klasik’ sudah tidak mempan. Maka sarkasme sang dalang genre sekarang agaknya tak bisa disalahkan.
Bila itu juga tidak mempan?
(kekurangan dan kesalahan dalam tulisan ini akan diperbaiki bila waktu telah memungkinkan)